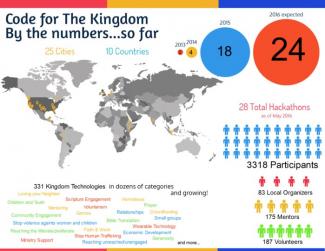Media sosial di Indonesia belakangan ini dibanjiri informasi yang membuat banyak orang tak nyaman. Informasi bernada provokatif, agitatif, hingga fitnah diunggah dan disebar dengan mudah tanpa mempertimbangkan atau menenggang hak dan perasaan orang lain. Tak jarang, informasi yang kerap tak jelas kebenaran dan sumbernya itu justru memicu putusnya silaturahim dan perkawanan.
Media sosial dipakai masyarakat untuk dua alasan, terhubung dengan orang lain dan mengelola citra mereka. Dar Meshi dkk dalam The Emerging Neuroscience of Social Media di Trends in Cognitive Sciences, Desember 2015, menyebut kedua alasan itu ialah kebutuhan dasar mansuia.
Sejatinya, keinginan manusia untuk terhubung dan mempertahankan reputasinya ada sejak awal peradaban manusia. Media sosial hanya mewadahi kebutuhan dasar itu hingga manusia bisa beradaptasi dan bertahan di lingkungan sosialnya.
Media sosial menawarkan kemudahan dan kecepatan menyebar informasi, memberi dan menerima tanggapan, mengamati peredaran informasi, hingga membuat perbandingan informasi yang ada. Karena itu, wajar jika media sosial jadi fenomena global. Saat ini, lebih dari 2,3 miliar penduduk Bumi memakainya.
Di Indonesia, media sosial turut mewadahi karakter bangsa yang kolektif. "Masyarakat Indonesia suka bercerita dan mendengar cerita. Mereka juga suka berbagi," kata ahli psikologi siber yang juga Ketua Program Studi Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Neila Ramdhani, Jumat (18/11).
Hal itu membuat media sosial diminati banyak orang di Indonesia. Wajar jika Indonesia jadi pengguna terbesar sejumlah aplikasi media sosial dunia 2016, seperti Facebook (peringkat ke-4) dan Twitter (3). Indonesia juga satu-satunya negara yang media sosialnya masih didominasi BlackBerry Messenger (BBM).
Belum bijak
Meski bagi sebagian orang penggunaan media sosial jadi kebutuhan sehari-hari, mayoritas orang Indonesia belum bijak memakainya. Dengan mudah, mereka mengunggah dan menyebar informasi tak jelas sumber dan kebenarannya atau informasi tak patut. Tak jarang, informasi yang disebar berisi provokasi, hasutan, atau fitnah.
Banyak pengguna media sosial enggan mengecek atau menilai kepantasan informasi yang diterima. Padahal, itu bisa dilakukan dari telepon atau komputer yang dipakai untuk mengakses media sosial.
"Mereka ingin jadi sumber informasi pertama sehingga langsung menyebarkan informasi, tak peduli benar atau salah," ujar Neila. Apalagi, penggunaan internet kerap memunculkan efek tak bisa mengendalikan perilaku di dunia maya (online disinhibition effect) sehingga norma di kehidupan sehari-hari seolah tak berlaku di dunia maya.
Selain itu, keinginan untuk jadi sumber informasi itu kadang menunjukkan masalah psikologi yang mereka hadapi, seperti ketidakpercayaan diri, mudah kagum, hingga cerminan ada orang-orang yang tidak terakomodasi dalam sistem sosial.
Ahli neurosains yang juga Kepala Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi Manado Taufiq Pasiak menilai, kecenderungan warga menyebar informasi yang belum tentu benar di media sosial adalah cerminan masyarakat kompulsif (compulsive society), berulang-ulang melakukan sesuatu demi meredakan kecemasannya.
"Makin menunda menyebarkan informasi yang dimiliki, termasuk untuk mengeceknya, mereka kian cemas," ucapnya.
Kecemasan itu muncul karena mereka tak terlatih berpikir. Ketidakmampuan berpikir membuat insting yang perlu tindakan cepat dan pragmatis, pemuasan segera dan jangka pendek, mendominasi. "Insting tetap diperlukan, khususnya menghadapi bahaya. Jika insting salah dipakai, muncul kecemasan," katanya.
Daripada menganalisis atau mengecek kebenarannya, mereka memilih menyebarkan informasi itu dengan harapan ada orang lain mengeceknya. Padahal, itu bisa memicu kecemasan massal, kepanikan, sikap apatis, hingga tak peka dengan informasi yang benar. Sikap itu berbahaya, terutama saat terjadi bencana.
Neila menambahkan, mudahnya warga menyebar informasi yang belum tentu benar menunjukkan rendahnya literasi digital mereka. Mayoritas pengguna internet di Indonesia ada di tahap literasi digital terendah, yaitu hanya punya kemampuan instrumental untuk mengoperasikan perangkat lunak di komputer atau telepon.
"Warga belum mencapai tahap mengevaluasi dan menghasilkan informasi hingga memahami tanggung jawab sosial atas informasi yang diakses, dimanfaatkan, dan dihasilkan," ujarnya.
Rentan konflik
Literasi digital itu tak berkolerasi dengan tingkat pendidikan formal atau status ekonomi. Karena itu, banyak orang pintar dan terdidik jadi tak bijak dan jadi penyebar informasi yang belum tentu benar.
Ketidakmampuan berpikir dan rendahnya literasi digital itu membuat masyarakat rentan mengalami konflik. Informasi itu mudah memicu munculnya penyakit hati, seperti iri, dengki, hingga kemarahan, dan akhirnya saling menghujat, memaki, dan tak percaya.
Nilai strategis itu membuat pengguna media sosial harus diatur. Jika itu tidak dilakukan, masyarakat akan mudah lelah dengan membanjirnya informasi yang sebagian besar tak jelas kebenarannya. "Media sosial rentan dimanfaatkan orang untuk membuat bangsa tidak stabil, mengganggu keamanan, dan ekonomi tak berkembang," tutur Neila.
Taufiq pun sepakat. Pengaturan itu bukan bentuk pengekangan kebebasan informasi. Fitrah manusia selalu ingin melampiaskan semuanya. Jika tak dibatasi, termasuk saat berpendapat atau menyebar informasi, kendali diri mereka akan hilang. Mereka bisa bertindak membabi buta, tak bisa menenggang rasa, bahkan jadi agresif.
Jika tak dikontrol, bangsa Indonesia bisa jadi masyarakat gila (madness society) yang hidup tanpa kendali dan memicu kekacauan bangsa. "Bangsa ini rentan terpecah belah bukan karena perbedaan suku atau agama, tapi kemampuan berpikir," katanya.
Oleh karena itu, revolusi pendidikan formal ataupun di rumah tangga harus dilakukan agar kemampuan berpikir rasional masyarakat terbangun. "Pemberdayaan fungsi eksekutif otak untuk menentukan pilihan dan melihat konsekuensinya, membuat putusan agar bisa memilih cepat dan tepat, serta mempelajari masa depan masih jadi persoalan besar di Indonesia," ujar Taufiq.
Sementara Neila melihat literasi digital harus segera diperbaiki. Kecerdasan dan emosi matang penggunaan internet harus dibangun, tak sekedar peningkatan infrastruktur internet yang baik. Dengan demikian, terintegrasinya antara pikiran, emosi, dan perilaku saat menggunakan teknologi informasi bisa terbentuk.
Diambil dari:
Nama surat kabar: Kompas
Judul artikel: Hasrat Menjadi yang Tercepat
Penulis artikel: M. Zaid Wahyudi
Tanggal terbit: 20 November 2016